IDENTITAS BUKU :
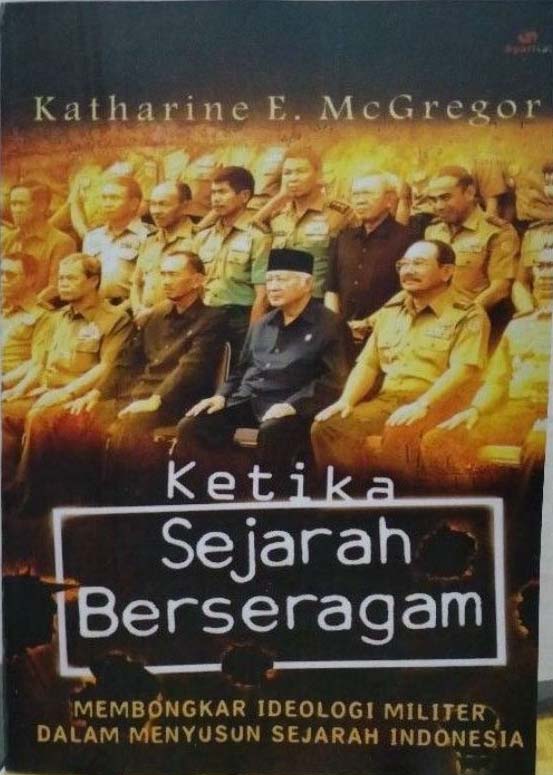
Judul Buku : Ketika Sejarah Berseragam : Membongkar Ideologi Militer Dalam Menyusun Sejarah Indonesia
Pengarang : Katharine McGregor
Penerbit : Syarikat
Tahun terbit : Mei 2008
Jumlah halaman : xxvii + 459 hal
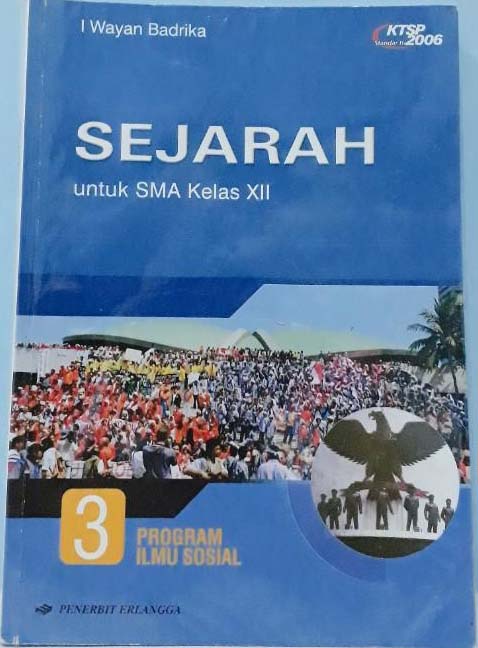
Judul Buku : Sejarah untuk SMA Kelas XII
Pengarang : I Wayan Bradika
Penerbit : Penerbit Erlangga
Tahun terbit : 2006
Jumlah halaman : vi + 282
Hitoriografi yang reflektif tidak saja
menguji secara kritis metodologi sejarah,
tetapi juga menguji dan merumuskan kembali berbagai klaim kebenaran
dan menyelidiki terbentuknya klaim kebenaran secara historis
(Henk Schulte Nordholt)
“Menghidupkan ingatan sosial bukan untuk menaruh dendam
dan benci pada kebrutalan kelompok tertentu di masa lalu,
tetapi lebih membangun proyek perdamaian
dan berusaha tidak mengulangi kekeliruan di masa lalu”.
(Paul Ricoeur)
Barangkali sedikit benar apa yang dilontarkan oleh Michael Sturner, bahwa kepentingan mencipta “sejarah” bagi setiap penguasa adalah lebih menggambarkan betapa penulisan sejarah dan cerita-cerita yang dibangun merupakan salah satu cara penguasaan “ingatan kolektif” massa rakyat. Bagi Michael Sturner “Di negeri tanpa sejarah, masa depan dikuasai oleh mereka yang menguasai isi ingatan, yang merumuskan konsep dan menafsirkan masa lalu”. Mereka yang dimaksud di sini tentu saja setiap penguasa yang memerlukan bentuk ‘legitimasi kekuasaan’ yang kuat dan permanen yang mengandaikan setiap dukungan pendapat umum untuk proses kelanggengan kekuasaan.
Mengetengahkan cerita-cerita dan gambaran-gambaran sejarah masa lalu bagi penguasa adalah penting untuk membangun wacana ‘ikatan relasioanal’ antara ‘yang silam’ dengan ‘yang kini’. Legitimasi ‘masa kini’ akan sangat ditentukan bagaimana ‘masa lalu’ kemudian dikonstruksi sehingga terbentang kesejarahan yang saling mendukung. Tidaklah mengherankan jika kemudian di mana-mana, penguasaan terhadap gambaran masa lampau dijadikan sebagai sarana pembenaran sistem yang dipakai sekarang. Sedikitnya ada 2 (dua) cara pengendalian narasi dalam sejarah yang juga berkait dengan modus kerja ‘narativasi’ dalam ideologi. Pertama, dengan penambahan unsur-unsur tertentu dalam sejarah. Praktik ini bisa dilakukan dengan pembuatan dokumen, buku sejarah, ataupun film yang mengisahkan keberhasilan, kejayaan-kejayaan dan tentu saja mitos-mitos yang selalu menyertainya. Kedua, bisa dilakukan dengan ‘kebisuan sejarah’ ini sangat menyangkut dengan pembangunan legitimasi. Sejarah yang bisa diakui benar hanyalah narasi sejarah yang disusun oleh institusi resmi yang ditunjuk negara. Ada banyak rahasia sejarah yang sengaja disembunyikan untuk kepentingan tersebut. Sering kali penguasa harus menggunakan payung aturan hukum yang resmi untuk mengontrol setiap usaha pembongkaran tersebut. Jika saja kekeliruan-kekeliruan dan manipulasi sejarah sampai terbongkar maka akan mengganggu legitimasi bagi penguasa.
Siapa yang mampu mengontrol dan mengatur wacana sejarah, dialah yang akan mampu membangun opini dan pendapat umum bagi masyarakat. Untuk kasus metode pertama pengendalian sejarah maka penguasa benar-benar akan sangat teliti dan jeli bagaimana narasi-narasi dalam sejarah itu disusun dan diolah. ‘penipuan’ (dissimulation) adalah salah satu modus operandi ideologi di mana relasi dominasi dapat dibangun dan dipelihara dengan cara disembunyikan, diingkari atau dikaburkan, atau dihadirkan dengan cara mengalihkan perhatian dari atau memberikan penjelasan terhadap relasi atau proses yang sedang berlangsung.
Masih cukup ingat ketika pemerintah melalui kejaksaan agung dibuat berang dengan hadirnya perubahan buku-buku sejarah yang tidak mencantumkan kata ”PKI” dalam peristiwa september 1965, pemerintah lagi-lagi dengan kencang mewartakan ’isu kewaspadaan’ akan bangkitnya ’komunisme baru”. Kontroversi itupun kembali muncul di tengah upaya para ahli sejarah dan kaum intelektual untuk membangun dan menata kembali sejarah yang sudah lama hidup dalam bayang-bayang kekuasaan. Polemik itu kembali muncul dan bergulir didorong oleh semakin terbukanya ruang untuk menafsirkan sejarah lebih demokratis dan berpihak pada masyarakat. Terutama sejak angin perubahan 1998, banyak komunitas korban memberanikan diri untuk terlibat memberi testimoni terhadap kekacauan sejarah yang kian waktu tunduk pada kontrol kekuasaan.
Buku “Ketika Sejarah Berseragam” karya Katharine McGregor tepat kiranya menjadi salah satu kajian yang amat penting untuk melihat historiografi sejarah Indonesia yang masih sarat dengan kekuasaan terutama kepentingan militer. Dalam berbagai catatan yang terbukukan sejak kekuasaan Orde Baru sampai sekarang, peran militer tetap masih selalu hadir dominan dalam panggung sejarah nasional Indonesia. Di dalam genggaman kekuasaan, sejarah bisa menjadi sesuatu sarana ideologisasi yang amat strategis. Dalam tangan besi kekuasaan, sejarah bisa akan menjadi sosok yang mempunyai dua wajah sekaligus. Wajah yang satu mendewakan fakta yang dianggap akan mendukung berjalannya kekuasaan dan wajah yang lain telah membenamkan fakta-fakta yang dianggap mengganggu legitimasi status quo. Akhirnya sejarah bagi kekuasaan tidak jauh dengan prinsip “pelanggengan” dan “pelenyapan”.
“Ketika Sejarah Berseragam” karya Katharine McGregor dengan jeli telah berupaya untuk mengungkapkan motif-motif dan kisah-kisah di belakang proyek-proyek sejarah yang diabngun militer. Bagaimana militer mampu dengan cerdik mengkonstruksi “masa lampau” adalah gagasan besar dalam buku ini. Buku ini sekaligus menggambarkan beberapa fakta perilaku politik di belakang “representasi” beberapa periode panggung sejarah yang penting di indonesia. Lebih jauh dari sekedar untuk menelisik dan sekaligus mengajak membaca “ingatan kolektif” tentang perjalanan sejarah Indoensia, McGregor justru sangat jeli untuk mengatakan bahwa sejarah indonesia selama ini tidak luput dari ketegangan-ketegangan dan proses-proses persaingan, dan dalam beberapa kasus adalah proses pembinasaan “sejarah yang lain”. Sejarah menjadi “berseragam” dalam pengertian sebenarnya karena kekuasaan mampu melekatkan upaya ini dengan berbagai kebijakan seperti pengendalian yang ketat terhadap media dan pendidikan, manipulasi pemilihan umum, kurangnya kebebasan berpendapat, dan tradisi menggunakan “militer” untuk menangani apa yang disebut sebagai “ancaman terhadap keamanan nasional”. Apa yang dianggap berseberangan dengan “sejarah resmi” akan segera ditutup, dilarang dan dibreidel.
Ketika “Sejarah” Tidak berpihak ke “Korban”
Pembredelan-pembredelan telah menjadi tradisi paling ”primitif” yang kerap harus dilakukan penguasa sejak negeri ini dibangun. Negeri ini katanya memang merdeka, tetapi warisan kolonial dengan ketatnya ”dominasi wacana” tetap disukai bagi rezim siapapun yang saat ini memimpin. Pola ini menjadi mesin berangus yang dianggap paling efektif; Pertama, bukan semata-mata pelarangan, pembredelan dan pembakaran fisik yang dituju melainkan efek teror yang ditimbulkan yang mampu membangun ’kewibawaan’ penguasa. Kedua, hilangnya kesempatan bagi interpretasi lain tentang ’kebenaran’ sejarah akan memudahkan mesin kontrol ’kaca mata kuda’ penguasa bekerja. Ketiga, penguasa semakin sadar bahwa ruang pengetahuan adalah modal dan amunisi paling menakutkan yang akan menjadi perintang mesin-mesin dominasi bekerja. Logikanya sederhana, seperti kembali pada jaman masa perbudakan bahwa yang dibutuhkan kelas pemenang bukanlah masyarakat budak yang pintar dan tahu posisi dirinya namun cukup mereka yang patuh dan loyal pada kekuasaan. Budak tidak perlu pendidikan apalagi harus menerima asupan gizi untuk berkembang. Ketaatan, kepatuhan, dan loyalitas buta adalah harga mati bagi siapapun yang ingin diperintah. Tentu saja, membuat masyarakat pintar justru hanya akan menjadi biang bumerang dan sumber kerepotan kelak. Sejarah tidak perlu dibuat warna-warni. Cukup dengan sejarah tunggal maka, penguasa bisa tidur nyenyak tanpa harus mengalami mimpi buruk untuk disalahkan masyarakat.
Mungkin saja negeri ini lupa atau tidak utuh membaca sejarahnya sendiri. Aturan dan kontrol represif apapun tidak bisa ’memenjarakan’ apa yang dinamakan gagasan ataupun ”interpretasi”. Seketat apapun penindasan justru akan memupuk lahan subur bagi munculnya benih-benih perlawann. Kalaupun letupan ini belum sebesar ledakan revolusi, ia sendiri akan melahirkan watak laten bagi kemungkinan perlawanan-perlawanan. Kemunculan ’sejarah-sejarah pinggiran’ hanyalah bagian kecil dari cara orang untuk melawan otoritas klaim kebenaran. Percikan-percikan dari ’tutur’ dan ’kesaksian’ para korban tentu saja bisa berpotensi menjadi ’mozaik’ dan ’orkestra’ solidaritas bagi ’suara-suara’ yang sampai saat ini terbungkam. Maka siapapun yang berkuasa akan sangat berhitung dan berhati-hati dengan semakin bergemanya ’sejarah-sejarah’ lain yang diusung oleh para saksi sejarah yang notabene telah lama disingkirkan dalam panggung sejarah.
Tentu saja apa yang menjadi dorongan para ’korban’ untuk menuturkan pengalaman sejarahnya bukan semata mata upaya balas dendam ataupun romatisme semata melainkan sebuah langkah memberikan warna sejarah menjadi berimbang. Tidak ada yang pernah salah dalam sejarah. Yang menjadi pembeda adalah ’keperpihakan sejarah”. Untuk kepentingan siapa sejarah kemudian ditulis dan dituturkan. Sebagaimana yang abadi adalah ’kontradiksi atas kepentingan ’ maka yang selalu akan menjadi abadi dalam setiap sejarah adalah konflik kepentingan itu sendiri. Setiap kelas sosial akan menyusun dan menggambarkan sejarah sesuai dengan basis kepentingan kelasnya sendiri. Bagi kelas yang mapan maka sejarah adalah tak ubahnya upaya membangun narasi-narasi pembenaran untuk mencari klaim keabsahan kekuasaan. Bagi yang kalah dan ada di ruang pinggiran, pentingnya sejarah tidak ubahnya untuk menjadi senjata bagi pembongkaran relasi-relasi yang telah mapan.
Ketika sebagian orang berharap pada proses ’pelurusan sejarah”, yang terpancar dalam harapan mereka tentu saja tidak hanya pada perubahan teks sejarah semata, teapi tentu saja lebih jauh dari itu adalah pembenahan nasib para ’korban’. Menuliskan sejarah bagi para ’korban’ adalah teriakan tuntutan atas pembenahan-pembenahan negeri yang selama ini telah banyak disalahgunakan atas nama kebenaran sejarah. Memang tidak begitu gampang untuk mendorong penguasa yang telah sekian lama menjadi ’narator tunggal’ dan begitu tuli untuk mendengar ’kisah-kisah’ yang lain dengan penuh kearifan. Pelurusan sejarah bisa menjadi ancaman dan sekaligus liang kubur yang sangat menakutkan. Mustahil bagi yang berkuasa untuk dengan sukarela menampilkan watak-watak aslinya bagi masyarakat. Tentu saja ’kebohongan’ akan selalu dihalalkan bila itu tidak kontraproduktif dengan capaian kekuasaan. Sedemikian memahami dan sadar akan ’rumusan’ ini maka segala apapun akan dilakukan walaupun itu harus mengorbankan banyak hal.
Di titik ini semakin bisa dibaca, kekuasaan akan selalu membutuhkan cara apapun untuk dilakukan. Kepentingan menguasai sejarah merupakan cara bagaimana bisa menguasai ingatan sosial masyarakat. Langkah inilah yang kemudian disebut Althusser sebagai mekanisme ’aparatus ideologis’ yang kerap bekerja pada ranah-ranah gagasan, pengetahuan dan kesadaran. Jika banyak orang sudah percaya buta walau apa yang dituturkan oleh ’sejarah resmi’ jauh dari kebenaran, sudah cukup menjadi modal untuk proses ’penaklukan’. Kekuasaan tidak lagi perlu menunjukan wajah angkernya dengan pelatuk senjata berulang-ulang. Apa yang dibayangkan Michel Foucoult bisa menjadi benar, pengetahuan bisa sangat efektif untuk membangun relasi kepatuhan. Jika sejarah adalah hal pengetahuan maka bagi pemilik kekuasaan rumusnya adalah ’pengetahuan haruslah dikuasai dan dijaga sebagai bentuk cara penjinakan masyarakat
Dialektika Sejarah : “Pelupaan” dan “Pengingatan”
Problemnya saat ini, jika mekanisme kekuasaan juga berjalan tidak selalu determinan seperti garis lurus dan mereproduksi dalam setiap relasi-relasi sosial yang terus dibangun, maka tentu masih banyak peluang untuk mencuri setiap ruang dari medan pertempuran ini guna membangun ’sejarah-sejarah lain’ yang berkontribusi untuk pelurusan sejarah. Maka tentu apa yang dibayangkan sebagai cara ’melawan teks-teks resmi sejarah’ bisa selalu dimungkinkan dimanapun dan kapanpun meskipun ruang dan kesempatan itu sangat sempit. Di sinilah peran ’kata-kata’ dan ’tulisan’ mendapat bumi pijakananya. Ia bisa lincah untuk menyuarakan apa saja yang saat ini dianggap bermasalah. Maka jauh-jauh waktu kekuasaan akan selalu membutuhkan senjata penjaga, penjara dan mesin-mesin pemusnah atas setiap potensi kemunculan ’kata-kata’ dan ’tulisan’ yang berbahaya. Namun apa yang dilantangkan oleh Tan Malaka barangkali benar, ”walau sampai dalam kubur, suara ini akan selalu terdengar”. Setiap gagasan dalam ’kata-kata’ akan mempunyai daya jangkaunya sendiri. Bahkan ia bisa melesat jauh melebihi usia generasi. Inilah kelebihannya.
Sejarah kembali lagi bisa menjadi medan pertempuran bagi yang berkuasa dan dikuasai. Ia selalu hidup dan berkembang dalam setiap tarik menarik kepentingan tersebut. Sejarah yang kalah kemudian akan selalu dipinggirkan dan dibuat untuk dilupakan. Sejarah yang menang akan dipuja-puja dan diperingati dalam setiap upacara-upacara dan menjadi ’bahan ajar’ dan ’matakuliah wajib’ bagi mereka yang menjadi objek dan sasaran kekuasaan. Sejarah yang kalah akan selulu ditutupi dan terus disengaja dilupakan. Kehadirannya adalah barang tabu yang bisa-bisa mengusik tatanan yang sudah mapan.
Dialektika sejarah dalam praktiknya selalu membawa pertarungan menang dan kalah. Bagi para pemenang, kisah yang bisa membangun legitimasi kuasa akan selalu dikenang dan dingat. Reproduksi fakta sejarah menjadi barang penting untuk dipompakan dalam kesadaran masyarakat. Seberapa jauh benar dan tidaknya, itu bukan menjadi barang penting. Bagi dasar kekuasaan, kebohongan sejarah tidak lagi menjadi sesuatu yang diharamkan. Ketundukan dan ketaatan adalah tujuan yang selalu ingin dicapai. Namun sebaliknya fakta-fakta sejarah yang tidak berkompromi dengan kehendak untuk kuasa akan selalu dikubur dan sengaja untuk dilupakan. Alih-alih membukanya untuk bisa dibaca sebagai keragaman sejarah, ”sejarah lain” adalah hantu yang bisa mengganggu tegaknya tiang-tiang penyangga kekuasaan.
Kebenaran sejarah tidaklah hadir dalam klaim-klaim dan jargon-jargon semata. Kebenaran sejarah tidaklah tunggal ia hidup dalam perjalananya yang lebih kongkrit. Problemnya, sejarah pinggiran kadang selalu tidak diberi tempat, walau kadang banyak kebenaran justru ada di sana. Sepantasnya bahwa membangun kembali sejarah merupakan dinamika kongkrit untuk membangun peradaban yang lebih adil. Rekonsiliasi sejarah selalu membutuhkan ruang-ruang demokratis bagi pengungkapan dan pelurusan sejarah. Walau proses ini selalu berhadapan dengan garis kekuasaan yang kadang bebal, upaya mendorong terciptanya kesempatan luas untuk adanya ’ruang tutur’ bagi pelurusan sejarah merupakan langkah awal yang sudah sangat baik.
Harapan besar bagi upaya merekonstruksi sejarah secara lebih benar tentu paling kongkritnya adalah bagaimana kemudian “sejarah” ditempatkan secara lebih benar. Dalam istilah yang lebih tepat seperti yang digagas oleh Heather Sutherland sebagai “historizing history” yakni menempatkan sejarah dalam konteksnya. Tentu upaya ini terkesan sangat utopis melihat bahwa negara sekaligus adalah ”medan” dan ”ruang” ketegangan yang detik ini belum menunjukan upaya keperpihakan pada berbagai kepingan sejarah pinggiran yang sekian waktu dibenamkan. Buku pendidikan sejarah pada umumnya juga masih menunjukan bias ideologis yang sangat kentara. Apa yang telah dipaparkan olej McGregor barangkali masih relevan, pendidikan sejarah dalam sekolah-sekolah masih lebih manampakan sebagai proyek ideologisasi ketimbang proyek pencerahan kesadaran kritis bagi siswa untuk memahami realitas hidup seharahnya secara lebih benar. Meskipun beberapa catatan metodologi pemaparan seharah mengalami perkembangan, pendidikan sejarah tetap saja cukup hati-hati dan bahkan menghindar untuk mengangkat “fakta-fakta kontroversial” yang detik ini masih belum. Dalam beberapa kasus seperti yang sepintas terlihat dalam buku pendidikan sejarah untuk SMA, sejarah-sejarah kontroversial yang seharusnya dilihat dan dibaca lebih proposional tetap saja diterabas sesuai dengan logika alur yang dominan dipakai dalam sejarah resmi sejak Orde baru. Ada fakta-fakta lain yang terus-menerus “disembunyikan” dengan berbagai pertimbangan yang lebih politis dan ideologis ketimbang alasan yang lebih objektif dan rasional. Sejarah masih tidak mendekat pada sejarah mereka yang pinggiran dan mereka yang selama ini dihilangkan dan historiografi indonesia. Sejarah lebih menjadi catatan peristiwa yang tidak dirasakan hidup oleh rakyat. Sejarah menjadi mengasingkan diri dari jantung cita-cita kesadaran sejarah sebenarnya. Satu faktor yang amat kentara adalah bahwa sejarah cenderung asyik berbincang hanya pada ”sejarah elite negara” dan sering berpaling pada ”catatan-catatan arus bawah” yang sebenarnya begitu amat kaya untuk dipaparkan. Sekali lagi, bukannya sejarah bukan semestinya hadir hanya untuk para pemenang..!!!
Sumber :
Majalah ISRA PUSHAM UII
Edisi 2, November 2008